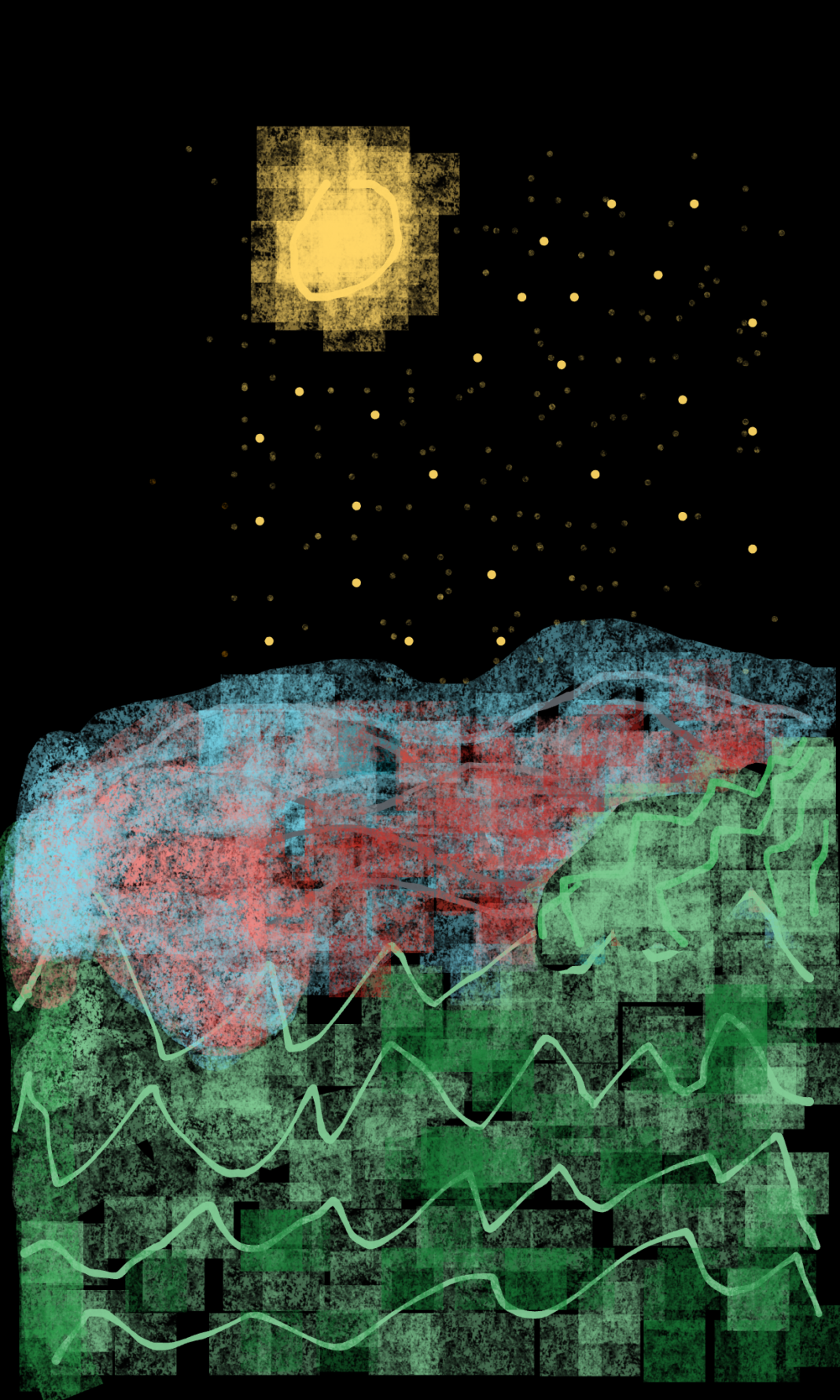Tuan-tuan tahu! Kalau sekarang kami hidup abadi, dapat merasakan yang namanya hidup bebas di tempat yang lebih pantas, yang tak pernah kami rasakan sebelumnya, dari negeri yang bahkan dahulu kami perjuangkan mati-matian dengan seluruh jiwa raga kami itu, yang nyungsep berdarah-darah hingga masuk berloncatan ke dalam anak sungai yang airnya berwarna merah.
Tuan-tuan tahu! Kalau kami tak sempat mencicipi masa senja yang tenang. Oh beruntungnya kami tak bisa menjadi tua walau usia telah merenggut semua umur kami secara paksa, menguburnya berpuluh-puluh tahun lamanya. Kami hidup di usia muda saja, tak bisa menua, dan bahagia selama-lamanya di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kami.
Kami tak akan lagi-lagi merasakan yang namanya, kesusahan hidup, dampak banjir di Jakarta, wabah malaria, atau jahatnya penjajahan yang dilakukan bangsa asing terhadap kami, yang luar biasa maha kejamnya menindas bangsa kami berulangkali itu. Terus terang kami heran, kenapa baru sekarang! Baru sekarang kami bisa merasakan perdamaian yang hakiki itu, kenapa tidak dari dulu-dulu saja! Kenapa perdamaian itu, tidak dapat kami rasakan ketika semasa kami masih hidup di negeri kelahiran kami itu.
Kami toh, tidak bertanya-tanya untuk siapa kami mati, dan orang-orang macam apa yang nanti akan mengelola negeri ini sepeninggalnya kami. Kami juga tak meminta! Untuk apa nama kami disematkan sebagai nama jalan. Kami hanya berharap, negeri ini mempunyai masa depan yang jauh lebih baik, daripada dijajah Belanda lagi.
“Tuhan maha baik ya, Bung,” kataku kepada Njunsang.
“Betul, ternyata ada loh tempat seindah ini, untuk kita hidup.” Mas’ud menimpali.
“Iya, malaikatnya juga sungguh baik, kita langsung disuruh masuk saja, gak perlu pakai diinterogasi segala, gak ditanya-tanya asal kita dari mana! Mereka langsung paham, lihat bercak darah di pakaian kita,” balas Njusang. “Rasa-rasanya baru kali ini, saya merasakan kemerdekaan yang paling merdeka.”
Sisanya tak bisa berkata-kata lagi, hanya mampu memandangi taman-taman yang indah itu, yang hijau segar, lalu cepat-cepat berlarian memasuki area itu untuk menemui gadis-gadis cantik yang bermata jeli, yang kulitnya putih secerlang keperak-perakan itu, yang rambutnya berwarna jingga dari cahaya senja, gigi-giginya seindah mutiara laut, dan harumnya seharum kembang kasturi.
Kami kira setelah perayaan kebebasan negara kami yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus, bangsa kami tak akan ditindas lagi dengan penjajahan dari bangsa asing mana pun, atau setidaknya semua bangsa-bangsa dapat saling menghormati kemerdekaan bangsa lainnya secara manusiawi. Ternyata tidak toh. Kenyataannya sejak kedatangan tujuh perwira Inggris, pada tanggal 8 September, yang dipimpin langsung oleh Mayor A.G. Greenhalgh, sebagai Allied Mission yang mendarat di lapangan terbang, Kemayoran.
Mimpi-mimpi kami tentang perdamaian, di negeri kami itu, ternyata hanyalah delusi semata. Kedatangan sekutu itu, belakangan kami ketahui, ditumpangi oleh Belanda yang punya maksud untuk berkuasa atas tanah air kami lagi.
Kami yang berjumlah tak lebih dari dua puluh orang, hanyalah sekumpulan pemuda-pemuda dari Kalibaru, Senen, Jakarta, yang ikut tergabung dalam organisasi Persatuan Rakyat Jakarta. Tepat pada tengah malam hari, yang bertepatan pada tanggal 20 November 1945, kami terbunuh pada pertempuran di tengah malam itu, yang tewas diberondong senjata mesin tempur yang berkekuatan tenaga siluman, oleh militer keji, tentara Belanda-Inggris.
Kami tahu kalau sebelum hari itu, kami disuruh minggat secara baik-baik, oleh karena pemerintah telah mengeluarkan instruksi untuk mengosongkan kota Jakarta, dari TKR serta laskar-laskar pejuang yang bertepatan pada tanggal 19 November, yang akhirnya para pejuang pun berbondong-bondong pergi angkat kaki, dari kota Jakarta menuju Karawang. Namun, beberapa dari kami menolak atas perintah itu, kami tampak peduli setan, sebab kami masih terngiang-ngiang oleh semarak suara kemerdekaan yang menggebu-gebu, riuh kebebasan yang saat itu sungguh sangat membakar semangat muda kami.
Sebuah kenangan dari perhelatan yang paling bersejarah bagi bangsa kami, yang kami kunjungi sendiri dengan kaki-kaki kecil kami, yang berjalan tak jauh bersebrangan dari tempat tinggal kami, di Kalibaru, tepatnya di daerah Menteng itu, di rumah milik orang Jepang itu.
Dan, belum lama ini, kami mendengar kabar bahwa sekitar seminggu yang lalu, di Surabaya, terdengar suara genderang perlawanan sengit yang berapi-api, turut menorehkan daftar pahlawan yang gugur bertambah banyak, konon katanya arek-arek Suroboyo bisa membuat ketar-ketir militer tentara Inggris-Gurkha, yang sok gagah-gagahan, yang datang bak pahlawan kesiangan itu, semakin memperbesar niat kami untuk bertempur habis-habisan di kota kelahiran kami ini.
Kami masih ingat betul, suara lantang dari Bung Tomo yang jargonnya, “Merdeka atau Mati”, kami masih ingat suara takbir dari beliau yang menggelorakan semangat kemerdekaan seratus persen.
Pada malam harinya, sebelum kejadian tragis itu terjadi, kami berkumpul di gang Sengon, untuk mengatur siasat, di rumah seorang pemimpin pemuda yang bekas jebolan dari Heiho. Di sana, kami yang bermodalkan senjata api Jepang jenis karaben arisaka, pistol, dan beberapa amunisi, membagikannya kepada sesama pemuda yang hadir di sana, dan sebelumnya juga turut ikut kami, merampas senjata-senjata itu dari tangan tentara Jepang, bersama kelompok pemuda dari Pasar Minggu, Kebayoran, dan Kebon Jeruk, pada tanggal 4 dan 29 Oktober 1945, di kediaman orang Jepang.
Aku memperhatikan dengan takzim, strategi gerilya yang diatur sedemikian ciamik oleh Bung Imam Syafi’i, orang Tanah Tinggi, yang pernah berkarir di organisasi semi militer, PETA, buatan orang Jepang. Setelah semuanya sudah bersiap-siap, penyerangan yang pertama kami, tertuju pada pos keamanan yang berada, di Tangsi Penggorengan. Kaki-kaki kami gentayangan, melangkah dengan mata-mata yang waspada, kami menyusuri jalanan tanah yang landai, mengikuti bayang-bayang pepohonan.
Dari arah belakang pos keamanan itu, kami melihat lima penjaga, yang berjaga dengan senjata laras panjang. Segera kami menjelma menjadi rerumputan, batu-batuan, dan gundukan semak-semak belukar. Dari balik bayang-bayang pohon beringin yang temaram, diam-diam kami merayap pelan-pelan. Di saat mereka lengah, dengan sigap kami menyergap tenggorokan mereka, seketika membuat mereka roboh di hadapan sebilah golok. Kami mengambil semua amunisi yang mereka punya, lalu menyembunyikan senjata-senjata mereka di dalam gundukan semak-semak belukar.
Setelah itu kami bersiap-siap untuk melakukan penyerangan kedua, ke tempat daerah Tanah Tinggi yang banyak pos keamanannya. Kami berjalan mengendap-endap, menyusuri aliran anak sungai yang banyak ditumbuhi pohon-pohon rindang, dan tanaman-tanaman perdu yang berduri.
Di tengah perjalanan, sayup-sayup dari kejauhan, kami mendengar suara truk patroli militer yang berkendara lengang sendirian. Segera kami menyelinap di antara pohon-pohon rindang yang teduh, bersembunyi dibalik rincik sungai yang tenang. Kami menunggu truk itu mendekat ke sisi-sisi sungai yang kami kuasai itu.
Sesaat truk patroli itu melintas perlahan, melaju pelan-pelan di hadapan kami, dengan sebuah isyarat tangan dari Bung Syafi’i, kami menerjang truk itu bertubi-tubi pada sisi bagian kanannya, menghujaninya dengan desing peluru yang menyala-nyala. Tiba-tiba saja, tanpa ada peringatan sebelumnya, dari arah yang berlawanan muncul sebuah iring-iringan kendaraan patroli militer lainnya, yang ngebut menghadang kami.
Kami tersentak, ketika iring-iringan itu mengeluarkan sejumlah gerombolan tentara-tentara berwajah bengis yang langsung membuyarkan kami, dengan rentetan suara tembakan. Kami diberondong secara membabi buta dengan peluru tajam tiada henti, membuat kami ngacir, berhamburan tak karuan, berlompatan ke sana sini, terjun ke anak sungai yang airnya beriak cipratan darah kami sendiri. Udara yang seketika itu, berubah menjadi bau mesiu yang bercampur dengan amis darah yang lembab.
Seorang di antara dari kami, masih ada yang mengepak-ngepak lemah di dalam air, sehingga mengaburkan desau rincik sungainya. Pada penyerangan kami yang kedua kalinya itu, kami benar-benar binasa. Tubuh kami tenggelam, lenyap ditelan oleh kelokan aliran sungai yang dalam.
“Itchang, kita kalah!,” teriak Mas’ud, saat ditikam peluru-peluru tajam Belanda di permukaan air, tanpa ampun.
“Tidak! Kau salah, kita merdeka,” sahutku sesaat hanyut ditelan air sungai.