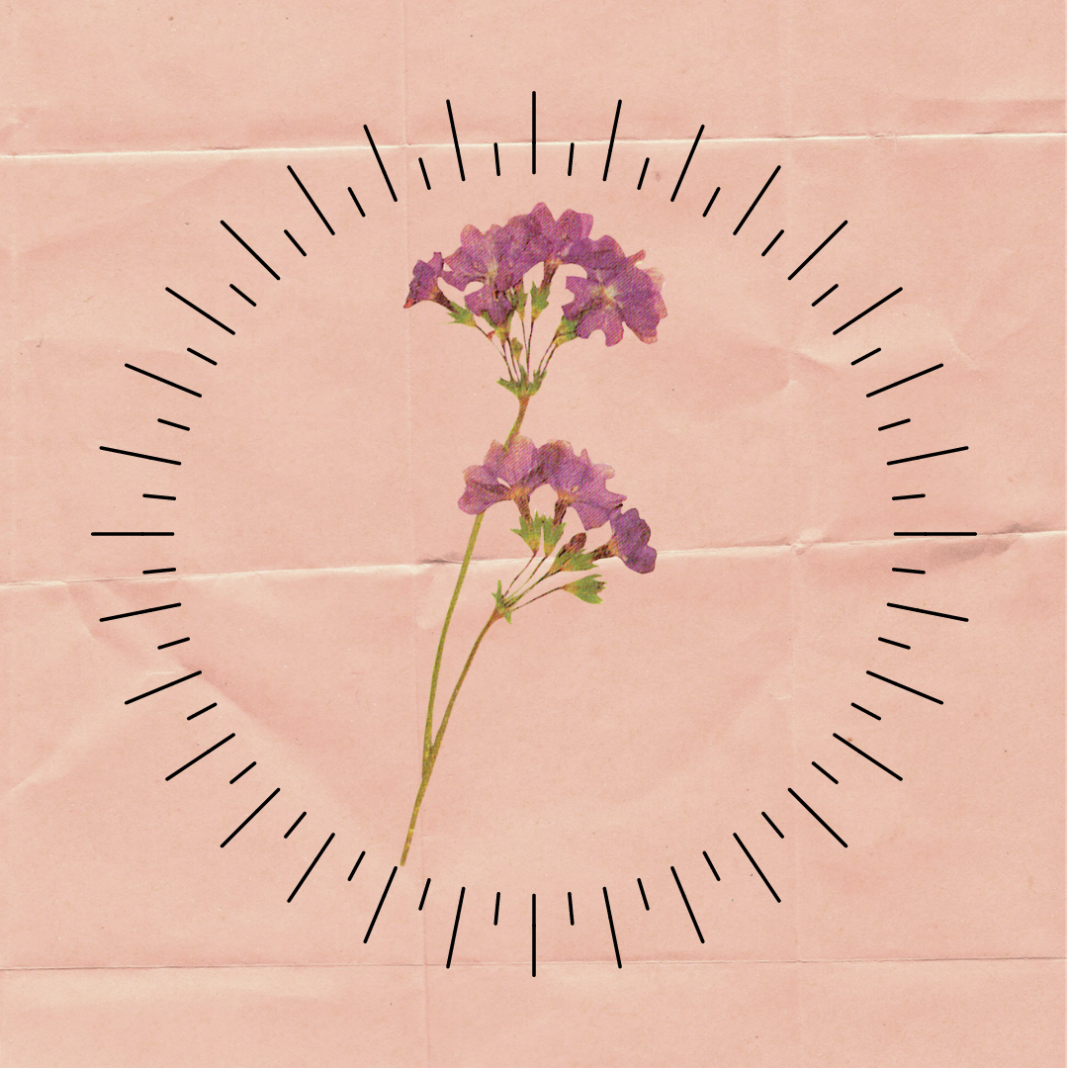Tulus si anak pemberani itu bangun lebih pagi dari biasanya karena hari ini merupakan hari penting baginya. Sebelum itu, dibuatkannya sang ibu yang masih tidur air hangat berisi seduhan teh yang dipercaya bisa memulihkan kesehatan wanita itu. Tulus lalu menyelempangkan handuk di pundaknya. Ia menyeret dirinya sendiri ke kamar mandi. Ritual setiap pagi yang paling malas anak kurus itu lakukan adalah mandi. Kadang ia pergi dari rumah tanpa membasuh diri. “Apa bedanya? Lagipula, mandi atau tidak aku masih terlihat kumal,” pikir Tulus.
Di gubuk kecil terbuat dari bambu yang lapuk dan sudah hampir rubuh, Tulus hidup bertahun-tahun hanya berdua bersama ibunya. Sudah empat tahun yang lalu sang ayah berpulang. Cerita mereka hampir mirip kisah-kisah penderitaan rakyat jelata lainnya, orang miskin seakan dibuat untuk dilarang sakit. Mungkin, jika mereka termasuk yang terkaya di desa ini. Sang ayah merupakan saudagar yang kaya raya. Hingga, pada suatu ketika, ia ditipu oleh sahabat karib yang juga koleganya. Singkat cerita, keluarga Tulus bangkrut.
Tulus masih ingat bagaimana ekspresi ayahnya saat meregang nyawa. Di kamar puskesmas yang berjarak dua setengah kilometer dari rumah Tulus, lelaki itu menutup mata tanpa sempat diberi pertolongan. Tulus hanya bisa mengintip dari balik pintu, lalu menangis sebelum sang ibu memeluknya. Andai saja mereka keluarga mampu, mungkin saja sang ayah takkan berlama-lama menahan sakit. Mungkin saja ia selamat. Tulus marah pada nasib yang menimpanya.
Kini Tulus dan ibunya harus berjuang mati-matian untuk menyambung nyawa. Sesekali Tulus menjadi buruh panggul di pelabuhan terutama di hari libur, sesekali juga Tulus berjualan emping buatan sang bunda di sekolah dan berkeliling di sekitar pemukimannya. Meski melelahkan, Tulus tetap bersemangat demi membantu ibunya serta demi menyambung hidup.
Tulus bersiap sekolah, memakai baju kebanggaannya yang sedikit kekecilan, menguning, dan penuh jahitan di sana-sini. “Nak, Ayah membelikanmu seragam. Sekolah yang baik dan pintar agar nasibmu lebih baik kedepannya,” pesan almarhum ayahanda dahulu kala, ketika Tulus baru masuk SD.
Diciumnya tangan sang ibu yang terkulai. Ia lalu mengangkat tangan sambil membacakan doa. Jika beberapa anak mendoakan orang tuanya kala mereka berangkat tidur, Tulus bisa berdoa untuk ibunya lima kali sehari. Ia tidak mau kehilangan ibundanya seperti ia kehilangan sang ayah. Kini, wanita yang telah melahirkan Tulus terbaring lemas setelah penyakit paru-paru menyerangnya sejak beberapa tahun yang lalu.
Sang ibunda terbatuk. “Sekolah, Nak?”. “Iya, Bu,” sahut Tulus sembari menalikan sepatu lusuh yang sebelah kanannya penuh tambalan sementara sebelah kirinya sudah menganga hampir lepas karena belum sempat ditambal.
“Kenapa pagi sekali hari ini?”
“Tulus tidak mau terlambat. Tulus dapat tugas membacakan karangan di upacara bendera hari ini, Bu,” anak itu mengucap dengan penuh bangga.
“Karangan apa?”
“Karangan buatan Tulus sendiri, Bu.”
“Oh, ya? Tentang apa, Nak?”
“Negara kita tercinta.”
Sang ibu tersenyum, sebelum mulai terbatuk lagi. Tulus mengingatkannya pada mendiang suami yang begitu nasionalis. Anehnya, nasionalisme sang suami tumbuh ketika mereka sudah jadi orang susah, dan itulah yang terus-terusan ia tularkan pada Tulus. Kadang perempuan itu heran, apalagi arti mencintai negeri sendiri sementara negeri ini saja begitu sibuk mencintai pemerintahannya, bukan rakyatnya. Tapi, almarhum suami pernah berkata, “Aku mencintai negeri ini seutuhnya, dan negeri aku yakin semua ini lebih dari sekadar orang-orang yang memerintah di ibu kota sana.”
“Tulus pergi dulu ya, Bu”
Sang ibu mengangguk. Anaknya keluar dari pintu anyam tanpa engsel. Pintu ditutup. Sang ibu kembali batuk, kali ini tiga kali lebih banyak sebelum langkah Tulus yang berat meninggalkannya sendirian.
***
Butuh sekitar satu kilometer berjalan kaki menyusuri jalan setapak untuk sampai ke SD Sumber Harapan. Dan di musim hujan seperti ini, kaki Tulus tak pernah berakhir bersih. Jalan setapak yang penuh lumpur yang cukup dalam selalu berusaha mencegah niatnya sekolah. Namun, Tulus tak pernah gentar. Apalagi, hari ini ada yang membuat Tulus lebih semangat dari biasanya. Pagi ini ia akan membacakan karangannya. Ia bangga, sekaligus gugup, Tulus mencoba membunuh rasa takutnya. Ia melangkah dengan dada terbusung, bagaikan sedang mengemban tugas yang sangat penting.
Di sekolah dengan atap yang sudah menganga, tembok yang hampir rubuh, dan papan tulis yang sudah retak dibagian tengah, Tulus dan kawan-kawannya yang tidak sampai ratusan berbaris manis di lapangan. Guru-guru yang jumlahnya bisa dihitung jari pun berbaris di depan.
Ibu kepala Sekolah berdiri di podium. Sebut saja podium, walau bentuknya lapuk dan kayunya terkelupas di sana-sini. Setelah berpidato, kepala sekolah mempersilahkan Tulus maju. Anak itu berdoa, menarik napas panjang, kemudian melangkah ke depan, tepat di sebelah podium kepala sekolah. Mata seluruh peserta upacara tertuju padanya. Dengan gemetar, Tulus mengangkat kertas dengan kedua tangan hingga setinggi dadanya.
“Wahai Dewi Keadilan, apa kabar? Apakah kau baik-baik saja? Sekarang sibuk apa? Begitu sibukkah sampai-sampai aku tidak pernah melihatmu berkunjung ke kehidupanku yang malang ini? Di mana kau berada saat keluargaku tidak dapat bantuan? Di mana kau berada saat aku kesulitan untuk bersekolah? Di mana kau berada saat aku kehujanan di kelas karena atap yang bocor.
Ku cari kau di tepi pantai, hingga ke kolong-kolong, tapi tak juga ku temui. Ataukah kau sedang sibuk mengurusi orang-orang kota, berkutat dengan kemewahan mereka? Ataukah kau memang tidak pernah ada, sebatas fiksi yang hanya bisa kulihat di layar kaca ajaib?”
Mata Tulus sejenak menyapu barisan teman-teman sekolahnya, sebelum ia meneruskan kata-katanya. “Ah, tapi, untuk apa juga kau berkunjung ke kehidupanku. Siapalah aku? Hanya anak kecil diantara ratusan ribu anak-anak lainnya yang tidak tahu apa-apa tentangmu.
Hanya satu dari banyaknya anak kecil mencoba memperjuangkan demi mendapatkan pendidikan, namun tidak tahu harus mengadu pada siapa jika suatu saat tidak bisa melanjutkan sekolah. Hanya satu dari sekian banyaknya anak kecil yang tidak mengerti…,” Tulus berhenti. Suaranya tercekat. Ia menelan ludah.
Para guru bergumam, murid-murid saling lihat. Tulus menarik napas. Ditahannya bulir air mata agar tidak menetes. Ia mendeham, tapi apa daya, tangisnya tak sengaja keluar. Tulus berusaha melanjutkan kalimatnya, “hanya satu dari sekian banyaknya anak kecil yang tidak mengerti bahwa wakil rakyat bisa berobat hingga pergi ke luar negeri sementara ibuku yang memang rakyat biasa tidak pernah mampu untuk mengeluarkan uang sekadar berobat.” Ia tidak pernah memikirkan betapa dalam makna kalimat tersebut ketika menulisnya beberapa waktu yang lalu. Pagi ini, saat keluar dari mulut kecilnya, kalimat itu terasa menusuk relung hati terdalam.
***
Selepas dari upacara, beberapa teman Tulus ada yang menertawakannya dan beberapa lainnya mengejek Tulus yang cengeng. Tapi, ketika murid-murid berjalan ke kelas, Birendra menepuk pundak Tulus.
“Kenapa tadi menangis?” tanyanya lembut. Padahal ia dapat menduga, kegundahan anak itu sebab oleh ibunya yang sedang sakit parah.
Tulus masih menundukkan kepalanya.
“Oh, ya, Bapak dengar dari Bu Tari, Ibumu sedang tidak sehat. Apa benar?” lanjut Birendra.
Tulus terdiam. Bingung menjelaskan bagaimana keadaan ibunya.
“Radang paru-paru, Pak”
Birendra terkejut. “Sudah diperiksa ke Dokter?”
Tulus menggeleng pelan. “Tidak ada biaya, Pak.”
Birendra menjadi cemas. Karena radang paru-paru itu dapat menular. Apa jadinya anak sepintar ini, jika sudah sulit keadaan ekonomi, harus juga disulitkan dengan kondisi kesehatan? Ia sedikit menunduk di hadapan Tulus, menyamakan tinggi mereka. “Kalau Bapak bawa ibumu ke dokter, bagaimana?”
Tulus terkesiap. “Jangan, Pak. Nanti merepotkan.”
“Tidak apa-apa. Nanti, sepulang sekolah, Bapak ikut ke rumah. Boleh?”
Tulus ragu-ragu. Takut Ibunya marah.
“Biar Ibu kembali sehat,” bujuk Birendra.
Tulus memantapkan hatinya pada pilihan yang diberikan. Lebih baik ibu marah tapi bisa kembali sehat. Tulus pun mengangguk.
✵✵✵
Tulus turun dari pijakan kaki sepeda. Kemudian, Birendra memarkir sepedanya di pagar kayu yang sudah sangat lapuk. Tulus membuka pagar rumah terbuat dari bambu, kemudian membuka pintu anyam yang tidak berengsel itu. Sementara Tulus masuk ke dalam, Birendra menunnggu di luar rumah.
Sambil memperhatikan rumah Tulus yang hanya sebatas gubuk bambu dengan rasa sesak. Pikirannya pun melayang, banyak anak yang pintar di negeri ini namun terhalang karena kondisi ekonomi. Dalam hatinya, ia bertekad akan mengusahakan beasiswa untuk Tulus, murid terpadai di kelas VI itu.
“Bu?” Tulus celingukan mencari ibunya ditempat ibunya biasa tidur.
Lalu Tulus cari ke belakang rumahnya. Ditemuinya sang ibu sedang mengupas apel di kursi kayu.
“Eh, Tulus. Bagaimana pembacaan karanganmu? Lancar? Ini ada kiriman apel dari tetangga. Cuci tangan, sana. Kita makan.”
“Bu, di depan rumah ada wali kelas Tulus.”
Sang Ibu terkejut. “Kau bikin masalah di sekolah?”
“Tidak, Bu. Tulus tidak bikin masalah. Pak Guru memang memaksa ingin menengok Ibu. Katanya, mau mengantarkan ibu ke dokter.”
Ibunya mengernyit. Ia menaruh pisaunya, lalu berdiri, kemudian berjalan ke arah depan rumah. “Kenapa kau ceritakan kondisi ibu pada Pak Guru? Kau tahu, Ibu bisa mengurus diri sendiri. Jangan malah merepotkan orang lain.”
Tulus mengikuti dari belakang. “Bukan begitu, Bu. Kata Pak Guru masalah paru-paru bisa sembuh asalkan ditangani dengan cepat. Jangan sampai malah menulari orang-orang di sekitar Ibu.”
Ibunya tersontak, langkahnya terhenti. Sedari dulu, ia selalu meremehkan penyakitnya lupa apabila anak semata wayangnya itu dapat tertular dan tidak bisa melanjutkan sekolah, membuatnya takut sendiri. Ia memandang Tulus sambil mengusap pipinya. “Ibu tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Tulus. Tulus percaya itu, kan?”
Tulus mengangguk.
Karena Birendra mendengar suara percakapan dari dalam rumah, ia pun mengucapkan salam. “Permisi,” katanya.
“Ya, tunggu sebentar”. Sang ibu membelakangi pintu sambil menoleh.
Birendra dan perempuan itu bersitatap, lama, memastikan bahwa apa yang mereka lihat. Keriput memang menghiasi kedua wajah itu, tapi mereka tahu benar apa yang mereka lihat.
“Kau…” ucap keduanya dengan jari saling menunjuk.
Tulus berjalan ke arah Birendra. “Bu, ini wali kelas Tulus. Pak ini ibu Tulus.”
Seketika suasana hening.
“Pak? Bu? Kok, diam sih ?”, sambil melirik keduanya.
Birendra tersenyum. Sunny juga. Gadis yang ia kenal belasan tahun silam Tuhan pertemukan di tempat yang mengukir sejarah mereka.
Potongan teka-teki kehidupan yang selama ini hilang kini bersatu kembali.