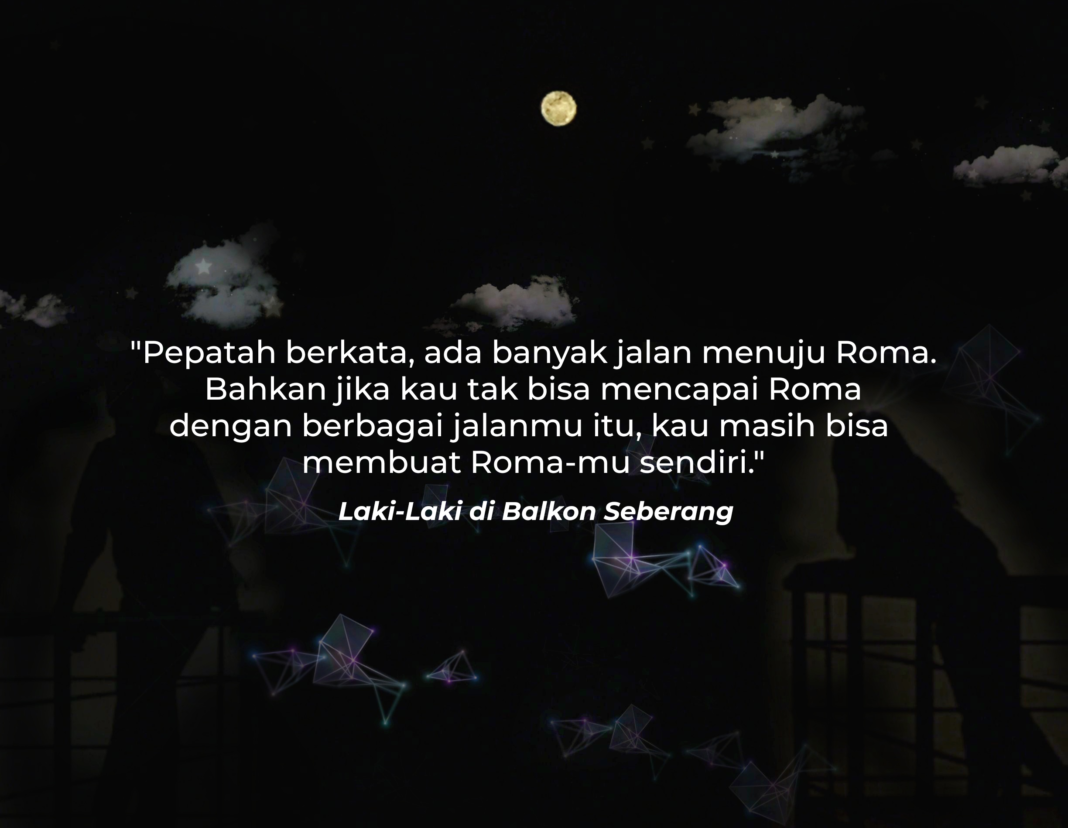Malam makin larut di Guanajuato. Heidi tak gubris dengan kehadiran angin yang berembus semakin kencang, semakin dingin––menyibakkan rambut ikalnya hingga acak-acakan. Kalau bagi orang lain ada dua musim, panas dan hujan, Heidi punya tiga: panas, hujan, dan insomnia. “Musim” insomnia kali ini mungkin adalah yang terpanjang bagi Heidi; tidur lelap di malam hari bagaikan privilese mahal yang tak dapat ia rasakan.
Sambil mengalunkan album Pink Floyd, Heidi bertopang dagu di teralis balkonnya. Matanya menjelajah setiap sudut jendela-jendela balkon pada bangunan di hadapannya, berharap menemukan manusia lain yang masih terjaga. Hasilnya nihil. Gelap. Tak ada tanda kehidupan.
Heidi kalut-marut; racun malam merasuki pikirannya. Segelintir ketakutan dan kecemasan pada dirinya bermuara pada malam itu. Tentang bagaimana realitas di masa mendatang akan memperlakukan segala mimpi yang ia bangun di masa kini. Tentang bagaimana ia akan gagal lagi, hancur lagi, dan dipaksa untuk bangkit lagi. Tentang ini, itu …. Tak akan ada habisnya.
Kepalan tangan Heidi menghantam teralis balkon. Ia benci menjadi seorang pesimis.
“Aku juga pernah melewati fase-fase itu, Kawan.”
Suara itu datang dari balkon seberang. Menggelar. Seseorang terjaga! Samar-samar, Heidi dapat melihatnya. Seorang laki-laki berpostur jangkung dan berparas wajah tajam khas Mediterania. Selama bermalam-malam menjadi “pengamat” balkon, Heidi sama sekali belum pernah melihat orang itu–entah karena orang tersebut adalah pendatang atau karena Heidi selalu saja sibuk menenggelamkan diri dipikirannya.
“Detik ini, kau tak lebih dari orang asing di seberang balkonku. Begitu pula dengan aku. Bahkan aku tak mengerti apa yang sedang aku lakukan! Tetapi aku ingin mengatakan sesuatu. Mungkin aku tak cukup tahu mengenai dirimu untuk menghakimi, tetapi aku tahu bahwa setiap manusia bertanding dengan penderitaan mereka masing-masing. Kuharap kau dapat menaklukkan itu dan mendapatkan ketenangan jiwa. Semoga Tuhan memberkati.”
Heidi tak berkutik. Terdiam. Perlahan ia memberanikan diri untuk meluruskan pandangannya ke arah balkon di seberangnya, mematikan turntable, berdeham, dan menelan ludah.
“Aku bertaruh kalau kau adalah cenayang!”
Heidi berucap dengan setengah berteriak–suaranya menggaung di antara dua bangunan berjarak lima meter itu. Tak heran, impresi pertama setiap orang ketika bertemu Heidi adalah: perempuan aneh. Si laki-laki – yang awalnya hanya berniat untuk menyapa tetangga melankolis yang tak sengaja ia temui berkutat di balkon pada jam dua pagi – kini tampaknya enggan untuk beranjak masuk. Si laki-laki terdiam, memicingkan kedua matanya. Dahinya berkerut. Samar-samar dari kejauhan, Heidi memainkan jarinya di atas teralis balkon, menunggu jawaban.
“Aku pernah punya mimpi … ” Si laki-laki memecah keheningan, menarik napas.
” … Dihancurkan oleh kejamnya dunia.” “Dihancurkan oleh keluarga sendiri.”
Malam itu, mereka tergelak kecil dengan miris, setengah teperanjat. Dunia memang lucu, ya?
Heidi tidak pernah menemukan yang seperti itu sebelumnya. Mungkin malam itu adalah petanda; pemecah keheningan antara Heidi, angan-angannya, bulan, bintang-bintang, dan gelap gulitanya malam. Bukan lagi musik Pink Floyd atau monolog Heidi yang kesepian dengan sang rembulan, kali ini, orang sungguhan. Malam-malam yang dulu hanya miliknya, kini ia bagi bersama orang asing di seberang sana. Heidi kini punya teman dan dia tak pernah sebahagia ini.
“Ceritakan kepadaku tentang dirimu,” Heidi menguatkan cengkeramannya pada teralis, mendorong tubuhnya ke depan agar bisa melihat laki-laki di seberang itu lebih jelas. Ia menganalisis setiap detail perawakan laki-laki itu dengan cermat.
“Aku Lazuardi. Hanya seorang migran dari Afganistan, kabur tiga tahun yang lalu. Pernah tertembak dua kali di bahu kanan dan lengan kiri … ” ia berhenti sejenak dan menunjukkan bekas luka di bahu dan lengannya, “satu karena aku pergi ke luar untuk mendapatkan makanan, satu karena aku … Bernafas, kurasa? Tapi tenang, aku masih hidup dan berambisi menjalani hidup untuk mewujudkan mimpi–ya, aku pernah bermimpi, pernah berkali-kali melihat mimpiku dihancurkan, tetapi, hei, aku masih bisa bertahan pada mimpi-mimpiku. Harta paling berharga di dalam hidupku,” laki-laki bernama Lazuardi itu tersenyum puas.
“Seberapa kuat daya tahanmu, Lazuardi?”
“Aku hanya menjalaninya”.
“Apa mimpimu?”
“Pergi kuliah. Menimba ilmu agar aku bisa berdedikasi bagi orang-orangku di Afghan. Dan kalau aku berkesempatan, mengunjungi tanah suci,” kemudian ia terdiam, sejenak. “Kawan, aku bersaksi, selama diriku masih mampu, aku takkan berhenti memperjuangkan mimpi-mimpiku.”
“Tapi, mengapa?”
“High risk, high return. Aku ingin high return itu. Aku sudah cukup kehilangan banyak hal.”
Ia kira Lazuardi tak akan mendengar ucapannya.
“Bermimpi itu menyeramkan, kawan,” ucap Heidi, menghela napas. Matanya menyisir cakrawala, memandang lekat bintang-bintang yang bertaburan.
“Bermimpi itu tidak menyeramkan. Semuanya akan baik-baik saja,” dalam selang waktu beberapa detik, Lazuardi tertawa hambar; lagi-lagi, ungkapan klise itu. “Mungkin tidak selalu — ada kalanya hal buruk terjadi. Tapi, itu hanya akan berlaku selama setidaknya satu atau dua hari di dalam hidup, bukan? Semuanya mungkin takkan selalu baik-baik saja, kau tahu itu. Akan tetapi, pada akhirnya, semuanya pasti akan baik-baik saja. Kau mengerti maksudku?”
“Tapi, bagaimana jika pada akhirnya semua hal,”.
“Maka itu bukan akhirnya. Percayalah. Kalau hari ini kau gagal, mungkin nasibmu di hari esok akan lebih baik. Kalau hari esokmu tak jauh berbeda dengan hari ini, masih ada hari-hari lainnya. Suatu saat, kau pasti akan menemui titik akhir itu,”
Semilir angin malam kembali menyapa Heidi, menerp pancaindranya dengan lembut, seakan-akan berbisik di telinganya dan membawakan pesan; kau hidup dalam realitas. Kau masih di sini, merasakan semua hal yang nyata. Selama kau masih bisa merasa, kau bebas meraih asa.
” … dan ketika perjuangan bersimbah darah dan keringatmu akhirnya selesai, semuanya akan berakhir indah.”
Heidi menatap Lazuardi lekat-lekat. Mungkin, ucapan Lazuardi ada benarnya juga.
Semuanya akan baik-baik saja, pada akhirnya. Jika tidak … Itu bukan akhirnya.
Untuk pertama kalinya, Heidi akhirnya dapat menghela napas lega. Ia dapat merasakan beban yang memberatkan dadanya sirna seperti angin lalu. Ia menatap rembulan — kini penuh dengan harapan — seakan-akan sinarnya menyelinap ke celah-celah pikiran Heidi yang berkabut.
Akhirnya.
Heidi bahkan tak cukup optimis untuk mengharapkan pertanda, tetapi kali ini pertanda itu datang. Ia serasa dilahirkan kembali. Hidup lagi.
“Terima kasih telah memberikanku alasan untuk mencoba lagi,”.
Maka pada malam itulah sang perempuan melankolis bersaksi untuk kembali mengejar takdirnya. Mungkin semua hal yang ia takutkan hanyalah bagian dari delusi miliknya yang tak akan terjadi di masa depan. Ia tak tahu apa yang menunggunya di garis akhir, tetapi ia harus tetap berjuang. Mungkin di garis akhir itu adalah semua hal yang ia impikan dan bukan kegagalan. Mungkin selama ini ia terlalu terpaku pada posibilitasnya untuk gagal, tanpa menyadari bahwa peluang untuk berhasil selalu ada, tak peduli berapa besarnya.
Apabila semesta berpihak kepada siapa pun itu, mimpi pasti akan teraih tanpa memandang presentase peluang; keajaiban selalu ada. Realitas di masa depan merupakan alur terkompleks yang tersusun melalui cara-cara teraneh yang takbisa kita bayangkan. Terkadang buah pikiran manusia melenceng jauh dari apa yang mereka harapkan akan terjadi pada hari esok, minggu depan, atau dua tahun lagi. Kini Heidi sadar bahwa terkadang pikiran adalah manipulator ulung yang paling wahid; maka ia mendengarkan kata hatinya, karena kata hati tak pernah berbohong.
Dan ketika sang matahari terbit di timur kaki langit, ia bukan lagi Heidi sang melankolis yang merenung setiap malam di balkonnya; dia sadar bahwa dirinya lebih dari sekadar itu. Dirinya yang lama telah hilang ditelan bumi ketika malam perlahan berganti ke pagi dan rembulan tergantikan oleh mentari. Sudah cukup bagi Heidi hidup dipenuhi kekalutan.
Sembari merapikan rambutnya, Heidi memusatkan perhatian pada dinding kamarnya, dengan tatapan penuh makna. Di dinding itu terpampang besar secarik kertas yang ditempel dengan selotip. Kertas itu berisi beberapa patah kata yang tampaknya ditulis dengan acak-acakan menggunakan tinta merah.
Por mi raza hablará el espíritu. UNAM 20.
Kata-kata yang selalu membuat Heidi bergetar. Ya, moto universitas impiannya. Hari itu, ia akan tes seleksi admisi untuk mereservasikan dirinya sebuah bangku di UNAM. Sebuah momen penentuan. Meskipun bukan titik akhir dari segalanya, momen itu merupakan batu tonggak penanda hal penting dalam perjuangan hidup Heidi.
Heidi tidak pernah mempercayai mukjizat. Heidi tak pernah berpikir bahwa setelah ratusan malam yang menguras jiwa dan tanpa tidur yang ia lewati, suatu hari pada titik penentuan ia akan pergi memperjuangkan mimpinya dengan perasaan sebahagia ini; setenang ini. Mungkin bagi sebagian orang, adalah perkara mudah untuk bangun di pagi hari dengan ambisi untuk merajut mimpi.
Akan tetapi, perkara mudah itu menjadi tantangan yang harus ditaklukkan mati-matian bagi Heidi. Ketika haknya untuk mendapatkan afeksi dari orang tua direnggut — sejak keduanya berpisah — hilang juga semangatnya untuk terus mengukir asa. Akan tetapi, hari itu, Heidi mendapatkannya kembali — bagian dirinya yang hilang. Rasanya seperti bereuni dengan teman lama.
Tak pernah terlintas di kepala Heidi bahwa mimpi yang ia tulis di dinding kamarnya akan terwujud. Tak pernah terpikirkan di kepala Heidi bahwa hal pertama yang ia lihat ketika membuka mata di pagi hari dan hal terakhir yang ia lihat sebelum ia terlelap di pagi hari juga — atau malam hari, terkadang — kini takkan lagi menjadi suatu angan, tetapi realitas yang dijalaninya. Tak pernah terlintas atau terpikirkan … Sampai hal itu terjadi.
Dua minggu setelahnya, tepatnya. Hari bahagia Heidi. Kursi itu berhasil ia reservasikan untuk dirinya. Hari itu, semesta berpihak pada sisinya dan mengizinkannya untuk berbahagia.
Akan tetapi, terdapat suatu hal yang mengganjal. Ada seseorang yang Heidi sangat ingin temui; sang laki-laki di balkon seberang, Lazuardi. Pertemuan malam itu adalah pertama dan terakhir kalinya Heidi berbincang dengan Lazuardi. Sejak saat itu, Heidi tak pernah lagi mendapatkannya menyahut dengan tiba-tiba dari ujung balkon ketika Heidi merenung di malam hari.
Bermalam-malam ia memberanikan diri untuk memanggil namanya sekali-dua kali, lalu berkesimpulan bahwa mungkin ia memang sedang tak terjaga. Malam-malam selanjutnya, Heidi memutuskan untuk tak melakukannya lagi. Ia mengerti tak semua orang memiliki “musim” ketiga sepertinya, dan ia tak ingin menganggu. Heidi ingin menemuinya di siang hari, tetapi niatnya selalu ia urungkan karena, ya, memangnya dia siapa?
Namun, rupanya, dewi keberuntungan sedang berpihak pada Heidi hari itu. Entah mengapa, tanpa sebab, hari itu Heidi memutuskan untuk mengunjungi danau yang sering ia singgahi. Benar saja; di sana, ia mendapati seorang laki-laki jangkung yang tengah duduk di bibir danau, membelakanginya. Ingatan Heidi masih segar. Figur itu adalah Lazuardi; sang laki-laki di balkon seberang.
Heidi menatap punggung Lazuardi sesaat dan maju beberapa langkah, mendekatinya. Mempertimbangkan apakah ia harus memecah keheningan dengan mengatakan sesuatu atau tidak. Mungkin Lazuardi tak suka jika Heidi di sini. Mungkin ia sedang butuh waktu sendiri.
Heidi baru saja berniat untuk memutar balik ketika Lazuardi menoleh dan dalam kecepatan milidetik menyadari presensi Heidi.
“Hai, kau lagi,” Lazuardi buru-buru berdiri dan tersenyum tipis.
“Hai, Lazuardi. Aku bisa pergi kalau kau ingin sendiri,” jawab Heidi. Ada keraguan di suaranya.
“Tak masalah, kawan. Jika kau memang ingin di sini, tetaplah tinggal.”
“Aku ingin melihat matahari terbenam,” seperti yang dilakukannya dahulu ketika pikirannya dilanda kekacauan; singgah ke danau sepanjang hari dan melihat matahari terbenam ketika senja datang. Tempat ini bermakna personal baginya.
“Aku juga,”
“Bagus,”
Dan duduklah mereka berdua di atas rerumputan yang basah berembun; di tepi danau, melihat cahaya keemasan matahari yang perlahan sirna ditelan bumi. Sulit bagi Heidi untuk tidak jatuh cinta dengan keindahan senja hari meskipun terkadang ia membenci senja yang mengantarkan kehadiran malam. Membawakan episode-episode melankolis meresahkan jiwa bagi Heidi yang tampaknya tak ada habisnya. Akan tetapi, untuk sekarang, semua itu sudah berakhir. Ia siap untuk membuka lembaran baru dalam hidup.
“Um, aku akan pulang. Besok,” Lazuardi tiba-tiba berkata, entah apa maksudnya. Membuyarkan lamunan Heidi dan membawanya kembali ke dalam realitas.
“Pulang?”
“Pulang,” tegas Lazuardi, “Kembali ke Afghanistan.”
“Aku rasa kau punya masa depan yang baik jika merintis kariermu di sini, Kawan.”
Lazuardi menggeleng, “Selama aku masih berurusan dengan orang-orang Taliban, tidak ada jaminan masa depan yang baik bagiku. Ataupun bagi orang lain yang bernasib sepertiku.”
Heidi tak berkata apa-apa. Dirinya tak mengerti semua ini. Ia menatap Lazuardi, menuntut penjelasan.
“Ketika adikku, satu-satunya anggota keluargaku yang masih bertahan dibunuh oleh orang-orang Taliban, aku tahu aku tak punya apa-apa lagi. Tak punya lagi tanggung jawab untuk melindungi seseorang atau hak untuk dilindungi seseorang. Aku bebas untuk melakukan misi apa pun yang kukehendaki. Aku ingin membawa perubahan bagi orang-orangku di Afghan, tetapi aku sadar gerak-gerikku terbatas karena selalu diawasi. Kemampuanku pun terbatas karena aku bukan seorang intelektual atau akademisi yang andal. Aku menginginkan pendidikan agar aku bisa mengabdi pada orang-orangku di Afghan dengan ilmu yang kudapat. Lantas aku mencari segala cara untuk keluar dari Afghan dan seperti yang bisa kau lihat pada saat ini, di sinilah aku berakhir. Selama bertahun-tahun aku bekerja keras untuk membangun keadaan finansial yang stabil demi mempersiapkan kuliahku di masa mendatang. Sekarang, aku rasa aku sudah siap untuk itu.”
“Tetapi, beberapa hari lalu aku mendapat kabar,” Lazuardi berhenti sejenak, berpikir. Ia melemparkan kerikil ke permukaan danau yang tenang, tampak sedikit frustrasi. “bahwa adikku masih hidup.”
“Kau bercanda? Aku tak mengerti maksudmu.”
Lazuardi tersenyum hambar. Ia menggelengkan kepala, kemudian mengangkat bahunya. “aku ingat jelas bagaimana mereka menondongkan senjata ke arah adikku dan membunuh nyawanya dalam hitungan detik. Aku ingat bagaimana aku berkompromi dan memohon kepada orang-orang itu agar tidak menyakiti adikku, tetapi tentu saja gagal. Semuanya masih tersimpan di ingatanku dengan jelas. Entah apa yang terjadi setelahnya, tetapi yang pasti kini adikku masih hidup, bertahan, di luar sana. Sendirian. Dia butuh perlindungan.”
“Bagaimana kau bisa tahu kalau memang benar adikmu itu masih hidup?”
“Aku dihubungi. Mereka mengirimkan video adikku dan memberikan ultimatum agar aku segera kembali atau dia yang akan menjadi taruhan. Mereka menginginkanku karena aku melakukan gerakan aktivisme terlarang dan aku akan berurusan dengan mereka. Mereka memanfaatkan kelemahanku untuk mengancamku. Aku tak bisa apa-apa. Jadi, aku harus kembali,’.
Heidi tak berkomentar apa-apa. Dirinya terdiam, tatapannya terpaku pada permukaan tenang danau, pikirannya berusaha untuk mencerna segala hal yang ia dengar. Matahari hampir terbenam seluruhnya dan semua hal di sekeliling mulai terlihat remang-remang.
“Kau melalui hidup yang berat. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan karena aku tak pernah merasakan berada di posisimu, tetapi kau hebat. Benar-benar hebat. Kau melepas semua hal demi orang yang kau sayangi. Kau bisa saja mengejar universitas itu, bukan? Tetapi kau memilih untuk mengurungkan niatmu. Apa pun keputusan yang kau ambil, aku mendukungmu. Aku harap kau selalu aman,”.
“Tidak apa-apa. Pergi ke universitas bukan tujuan utamaku. Kalau dengan cara ini aku akan bisa memberikan kontribusi bagi orang-orang Afghanku, mengapa tidak? Mungkin ketika aku kembali, aku bisa bernegosiasi dengan orang-orang Taliban. Membuat strategi baru. Atau melakukan hal-hal lain yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Apa pun itu, demi orang-orang Afghanku. Tak bisa dimungkiri bahwa di dalam diriku masih terdapat sedikit hasrat untuk mengejar mimpi seperti remaja-remaja lain pada umumnya, tetapi kemudian aku sadar bahwa sukses tidak selalu diraih melalui satu jalan. Pepatah berkata, ada banyak jalan menuju Roma. Bahkan jika kau tak bisa mencapai Roma dengan berbagai jalanmu itu, kau masih bisa membuat Roma-mu sendiri. Kau masih bisa bersinar dengan caramu sendiri. Itulah hal yang ingin kuyakini.”
Kata-kata laki-laki asing ini tak pernah gagal membuat Heidi terkesima.
“Sungguh, kau adalah anugerah Tuhan. Terima kasih sudah menguatkanku malam itu, meskipun kita tak saling mengenal. Mimpiku berhasil kuraih berkatmu. Aku harap mimpimu juga,”. Heidi tersenyum.
“Kawan, itu bukan apa-apa. Terima kasih pula sudah menerimaku. Ku kira kau akan buru-buru menghindariku ketika tahu bahwa aku berasal dari Afganistan.”
Heidi menggeleng, “tidak sama sekali, Lazuardi. Omong-omong, semoga beruntung dengan misimu. Berjanji kepadaku, kau akan menemuiku lagi dalam keadaan selamat? Aku ingin kita berteman, kalau kau berkenan,”.
Lazuardi di tertawa kecil, “tentu saja, Kawan. Andai saja waktuku di sini lebih lama. Namun, aku harus kembali,”.
Heidi mengangguk, menandakan bahwa ia mengerti.
“Omong-omong, aku tidak pernah tahu namamu,”.
“Heidi,”.
“Oh, ya, Heidi … Nama yang indah. Um, aku akan kembali ke apartemen sekarang. Jangan bilang kalau hanya aku yang akan kembali. Kau takkan bisa menikmati apa-apa di keadaan gelap seperti ini,”.
“Aku bisa melihat cakrawala malam melalui bangku VIP di balkonku. Jauh lebih baik dari ini,”.
Mereka berdua tertawa. Dan malam itu adalah kali terakhir Heidi bertemu dengan Lazuardi, setidaknya untuk sementara waktu. Siapa sangka bahwa tetangga atau orang asing mana pun yang tak kaukenal dapat memberikanmu sejuta pelajaran berharga yang dapat mengubah hidupmu selamanya? Karena, ya, pada beberapa kasus itu terjadi, meskipun tak sering. Heidi bersyukur menjadi salah satu dari sedikit yang mengalami itu; ia bersyukur atas laki-laki di balkon seberang yang ia temui pada malam itu dan tak akan melupakannya selamanya.***
Raihanah Nabilla Firsty Rahman