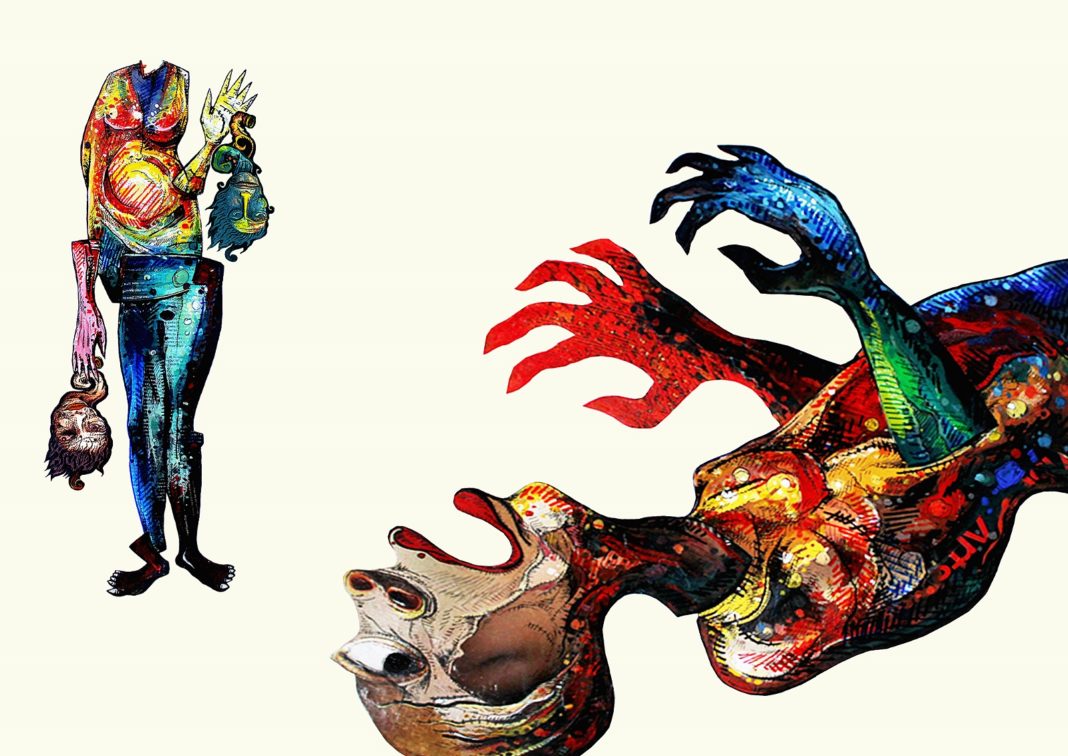Kami dipaksa menganut agama resmi, mencantumkannya di KTP, dan dipaksa menjauhi Tuhan kami— Dewata Sewwae, tentu kami tidak berdaya lantas harus menerimanya dengan dada lapang yang perih. Jumat, pada akhir tahun enam puluhan, pada siang yang hujan, segerombol tentara mendatangi Uwak—tetua yang dipercaya akan menyelamatkan orang Tolotang saat hidup dan setelah mati. Aku bergegas menuju bilik.
”Uwak harus memilih, atau hak sebagai warga negara tidak kalian dapatkan, bisa saja diusir, bisa saja ada yang bertindak di luar kendali, Uwak sudah tahu sendiri, bukan, apa yang akan terjadi?”
Aku mendengarnya dari balik bilikku yang hanya disekat dengan pembungkus semen setelah direkatkan pada tiang-tiang bambu dengan ramuan rebusan sagu. Aku anak Uwak satu-satunya–dan aku lebih banyak tinggal di dalam bilik. Percakapan Uwak dengan tamu-tamunya, jika tak boleh kusebutkan selalu–aku menjamin, hampir semuanya kudengarkan.
Cukup, Uwak, cukup! batinku.
Aku tidak ingin ada korban lagi. Dewata Sewwae begitu mencintai kita, sehingga Ia menguji seberapa kuat kita bertahan, Uwak pernah mengatakan itu padaku pada suatu malam, di dalam hutan, saat pelarian kami menjauhi pasukan gerilya yang membakar kampung kami. Di antara pasukan itu, ada kau salah satunya, Upe, lelaki yang berjanji akan menikahiku setelah kemerdekaan berhasil direbut dari tangan penjajah.
Sekalipun pernah kau katakan bahwa setelah tugasmu membela negara selesai, kau akan kembali menemaniku mengabdi pada Dewata, kenyataan yang kudapati sungguh berbeda; kau harus membunuhku dan aku tidak pernah lagi bertanya apakah kau masih mencintaiku atau tidak setelah malam tujuh Agustus 1954. Malam yang tidak akan kulupakan. Tepat setahun ketika pimpinanmu—dan kau, tentu saja, sebagai bagian Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan menyerukan perlawanan terhadap pemerintah. Sungguh, tidak perlu kau jelaskan alasannya; aku tahu kalian ditolak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia. Semua itu jelas, kau, dan kawanmu yang lain tak lolos administrasi. Kau sendiri yang bercerita padaku sehari sebelum kau ikut berjuang keluar-masuk hutan. Ada yang perlu kau jelaskan melebihi semuanya, ada yang masih terus mengganggu hingga pada pelarianku menjauhi maut aku masih terus bertanya; bukankah kita saling mencintai, kenapa kau ingin membunuhku tanpa alasan yang dengan mudah bisa kumengerti? Apakah hanya karena Tuhanku dengan Tuhan yang diakui negara kita berbeda?
”Kau pulang, Upe, akhirnya,” sambutku malam itu. Dan kupersilakan kau masuk begitu pintu rumah panggungku yang menimbulkan derit kasar terbuka.
”Di luar dingin, kalau malam, ya begini. Siang, panasnya minta ampun.” Dan kupikir gerilyawan seperti kau akan merasa kalimatku tadi adalah basa-basi paling lucu.
Akhirnya kekasihku pulang, gumamku dalam hati. Belum selesai kurayakan kebahagiaan itu dengan cara berdiam menatap wajahmu yang tirus dan lekang—belum habis kutatapi bola matamu yang tidak sejernih dulu, sesuatu menghunjam dadaku. Kau memoporku dan begitu aku terhuyung-terempas ke lantai papan, kulihat kau mulai mengarahkan moncong senapanmu ke tubuhku. Sekilas kulihat beberapa anak buahmu mengintip di celah jendela.
Masih sempat kulihat matamu. Masih sempat kulihat air yang hampir menetes ke pipimu, dan masih sempat kusebut namamu, menyadarkanmu, selalu kusempatkan; Upe, sadar!
”Mateko!”
Kau membentak sekaligus menyumpahiku segera mati dengan bahasa Bugis yang kasar.
Suara letusan senapan terdengar. Tiga kali tembakan dan kau sepertinya lupa cara mengenai sasaran dari jarak tiga meter, semuanya meleset. Namun, aku tidak ingin bertaruh lantas menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berdiri menjelang tubuhmu yang geming. Sejenak, aku menatap matamu lagi, berusaha menerka sisa-sisa cinta yang ada. Kita sama-sama diam. Hingga beberapa saat air mataku akhirnya jatuh karena tangisanmu yang tanpa suara. Aku jauh lebih mudah menemukan penyesalan dibanding cinta di matamu—yang dulu membuatku tergila-gila dan membuat kita sempat berjanji untuk hidup bersama, selama yang kita bisa untuk bertahan hidup.
Semua berubah, kau berubah, dan aku harus menerima kenyataan bahwa kau mungkin tidak punya cinta lagi setelah malam ketika aku kehilanganmu. Kehilangan dirimu yang dulu, maksudku, Upe.
”Lari,” bisikmu lirih dan aku bergegas membangunkan Uwak kemudian kami lari lewat pintu belakang ke arah hutan tanpa pernah tahu akan berakhir di mana.
”Dewata Sewwae begitu mencintai kita, sehingga Ia menguji seberapa kuat kita bertahan,” lenguh Uwak begitu langkah kami yang payah terhenti lantaran kehabisan tenaga.
”Uwak, ayo jawab!”
Aku tersentak, Uwak dibentak dengan keras oleh tentara itu. Aku jelas mendengarnya dan hal itu melamurkan ingatanku tentangmu dan malam yang memisahkan kita itu, Upe.
Setelah tiga belas tahun, kini kami seluruh penganut kepercayaan Tolotang harus kembali berhadapan dengan keresahan-keresahan dan ingatan-ingatan mengerikan. Tentang aroma daging bakar dan anyir darah yang tercecer di sekitar rongsokan bekas pembakaran rumah, dan tentang sungai yang ikannya tidak ingin dimakan penduduk sekitar karena dipercaya memakan daging manusia.
”Kalian siapa?” balas Uwak dengan bentakan, ”sopan santun bertamu belum tahu, ha? Ini rumah saya, sopanlah. Atau saya usir?”
Aku tahu jelas bagaimana watak Uwak, keras, sebagaimana imannya pada ajaran Tolotang. Aku sedikit beringsut, membetulkan kerah daster yang bertahun-tahun lalu kau hadiahkan saat kau masih bertani. Di sudut bilik ada celah untuk mengintip akibat sekat bungkus semen yang robek. Aku melihat ada tiga orang berpakaian loreng yang duduk bersila. Seorangnya lagi, juga bersila, tidak dengan pakaian loreng, melainkan dengan sarung yang ia sampirkan ke pundak, dan peci berwarna hitam, lintingan tembakau terjepit di antara telunjuk dan jari tengahnya—dia Uwak.
Tampak seseorang yang kuduga paling tua dari ketiga tentara itu berdeham lalu menenangkan Uwak.
”Kami sedang bertugas, Uwak,” jelasnya, lebih lembut dari rekannya, ”kami sedang mengadakan operasi malilu sipakainge, kami hanya menjalankan perintah,” sambungnya lantas berdiri diikuti yang lain sambil tersenyum sinis mengucapkan: kami akan kembali membawa berkas buat diteken.
Selama hampir sebulan aku dan Uwak bertahan di gubuk sederhana yang kami bangun seadanya di dalam hutan sebelum Uwak memutuskan untuk mengunjungi kerabat di Sengkang—yang mujur bagi kami, bersedia menampung. Kami berpindah-pindah, dari kerabat yang satu ke kerabat yang lain. Dari Sengkang, Soppeng, Bone, dan sempat pula beberapa bulan di Ujungpandang, rumah keluarga Ibu. Tidak perlu kau bertanya soal kabar Ibu, Upe. Aku tahu, kau tak mungkin luput mendengar berita istri ketua adat Tolotang yang ditemukan kepalanya oleh warga, di sungai yang membelah kampung kita. Berita itu belum juga reda ketika kau mendatangi rumah kami dan memopor dadaku yang sampai hari ini masih menyisakan luka. Luka yang sembuh—dengan rasa sakit yang tidak pernah hilang.
”Isuri!”
Kudengar Uwak berteriak dari ruang depan. Aku bergegas.
”Kita harus siap,” bukanya, ”demi Dewata Sewwae, kau juga siaplah,” ia menekan di kata-kata terakhirnya. Aku sudah paham apa yang ingin Uwak lakukan. Dia akan menolak memilih agama selain Tolotang. Tentu kau tahu, di saat seperti inilah aku akan mudah mengingatmu, Upe; apa kabarmu? Kau di mana? Dan, o iya, sudah berapa anakmu sekarang? Atau masih tetap sendiri sepertiku, bahkan pada usia yang menuju kepala empat ini. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku tidak sadar Uwak telah merangkulku.
”Saya tahu yang kau pikir, Isuri.” Uwak menepuk halus pundakku. ”Kita sudah kehilangan banyak orang, bahkan Ibu kau sendiri. Jangan setengah-setengah buat Tuhan.”
Aku tidak sanggup menahan air mata yang kuduga kini telah basah di lengan Uwak. Terisak. Dadaku sesak.
”Cukup, Uwak,” ucapku terbata-bata di sela tangisan, ”turuti saja mereka itu, jangan korbankan siapapun, sudah cukup. Lagipula Dewata Sewwae tidak peduli KTP kita, Uwak. Agama apa pun yang ada di KTP, selama kita menyembah dan beragama dengan cara Tolotang, tidak akan jadi masalah.”
”Pikirlah dulu, Isuri,”
”Tapi, Uwak—”
”Saya belum selesai,” sanggah Uwak, ”lebih baik ditembaki tentara daripada dibunuh orang-orang di kampung ini. Lebih baik menodai aturan pemerintah daripada menodai agama orang lain, paham?”
Aku mengangguk lemah, namun tetap saja aku tidak setuju untuk melawan pemerintah, aku bisa apa, aku lebih tidak berani melawan Uwak.
Dua tahun lalu, aku berunding setegang ini bersama Uwak. Kami harus memutuskan kembali ke Sidrap atau tetap merepotkan kerabat Ibu di Ujungpandang. Uwak menimbang, aku memperhitungkan. Sehari sebelum perundingan untuk menentukan sikap itu, ada kabar menyenangkan sekaligus membuatku meresahkanmu, lewat radio dan selebaran yang disebar. Bahkan toa masjid tidak luput memberitakannya. Tanggal 3 Februari 1965, di dalam hutan—tubir Sungai Lasolo, orang-orangmu mati ditumpas pasukan kiriman pemerintah—yang akhirnya juga mengirim orang-orangnya untuk menumpas kepercayaan kami.
Hujan belum berhenti. Sebentar lagi tentara itu datang, dan kami harus memilih.
”Pilih saja, Uwak,” bujukku.
”Mau berjanji?”
”Apa pun, demi Uwak, demi Dewata Sewwae.”
”Apa pun agama di KTP, kita harus tetap Tolotang.”
Kami sepakat, dan ketika tentara datang, Uwak tidak banyak bicara sebelum dan setelah meneken surat pernyataan.
Sudah sepuluh tahun berlalu setelah KTP kami resmi berubah. Aku masih menunggumu datang, Upe—begitu juga Uwak. Kini ia terbaring lemah di ranjang kami, batuknya semakin parah, kobokan yang kuisi pasir untuk wadah ludahnya yang bercampur darah sudah sangat amis. Beberapa saat, berselang setelah batuk yang panjang, Uwak mendoakan kebahagiaan buat pernikahan kita yang sepuluh tahun lalu kujanjikan buatnya. Doanya yang terakhir.
Air mataku jatuh, aku menyesal membohonginya.
Kami akan menikah, dia akan datang, dan jika kita tidak mengikuti pemerintah, artinya kita cacat administrasi. Pernikahan kami akan susah, orang kampung tidak akan sepakat, dan kami tidak akan tenang, Uwak. Kumohon, mengertilah, memilihlah. Aku membujuk.
Uwak luluh. Demi kebahagiaan kita dan demi kau yang akan menjadikanku istri. Sejak hari itu kami menunggumu, Upe. Meskipun aku tidak pernah tahu kau selamat atau tidak saat penyerangan 3 Februari 1965.
Keterangan:
Tolotang, kepercayaan tradisional di Sulawesi Selatan yang merujuk pada arti orang-orang dari Selatan.